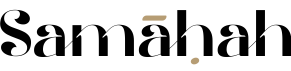Konsep wasathiyyah dapat diimplementasikan dalam keseluruhan aspek kehidupan dan salah satu aspek kehidupan adalah religi. Kebebasan beragama merupakan prinsip penerimaan.
Penerimaan di sini berarti kesediaan menerima dan menghormati perbedaan agama dan termasuk di dalamnya budaya agama. Setiap pemeluk agama di negeri muslim benar-benar menghargai agamanya sendiri kemudian menghargai keberadaan agama lain. Agama bukanlah sumber perpecahan melainkan pilar persatuan.
Ketika perselisihan terjadi antaragama, timbul permusuhan dan keengganan memahami agama seseorang karenanya ini akan mengakibatkan pertumpahan darah, seperti yang terjadi pada muslim Rohingya di Myanmar.
Indonesia merupakan negara dan bangsa yang masyarakatnya menganut multiagama dan mereka hidup dengan cara yang berbeda-beda. Maka saling menghargai dan menerima perbedaan merupakan keniscayaan. Kehidupan semacam ini meneladani apa yang telah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW ketika membangun Kota Madinah di bawah konstitusi Madinah.
Konstitusi Madinah ditandatangani Nabi SAW dan komunitas nonmuslim dan menghidupkan kembali semangat toleransi dalam mengamalkan agama masing-masing. Oleh karena itu, dengan Piagam Madinah, masyarakat Madinah dari berbagai ras hidup rukun dan saling menguntungkan, saling menghormati, meskipun agama yang dipraktikkan berbeda-beda.
Nabi SAW memberikan kebebasan beragama kepada mereka yang bukan dari keyakinan Islam. Hal ini sejalan dengan nasihat Allah SWT: “Tidak ada paksaan dalam agama. Telah nyata kebenaran dari kesalahan. Barangsiapa menolak kejahatan dan percaya Allah maka ia telah menggenggam pegangan dengan tangan yang kokoh yang tidak akan pernah terputus. Dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 256)
Menurut keterangan sebab turunnya, ayat ini diturunkan kepada penduduk Anshar di Madinah. Pada saat itu, banyak dijumpai di kalangan penduduk Anshar yang memiliki anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka telah menjadikan anak-anak mereka penganut agama Yahudi atau Nasrani, dua agama yang mendahului Islam.
Ketika Allah menyampaikan risalah Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, penduduk Anshar ini mempunyai keinginan untuk memaksa anak-anak mereka yang sudah beragama Yahudi dan Nasrani itu masuk dan memeluk agama baru, Islam. Sebagai jawaban dan penjelasan atas keinginan mereka untuk mengonversi putra-putri mereka ke Islam, turunlah kemudian ayat ini.
Intinya Allah melarang mereka melakukan pemurtadan secara paksa terhadap anak-anak tersebut agar pindah ke agama Islam. Siapa berkehendak ia akan menegakkan tauhid Islam dan siapa berkehendak ia dapat meninggalkan Islam.
Al-Ikrah dalam ayat itu bermakna paksaan (al-ijbar) dan tekanan atau beban (al-haml) untuk melakukan suatu tindakan dengan tanpa kerelaan. Al-ikrah adalah apa yang tampak dan berpengaruh pada perbuatan-perbuatan lahiriah dan tindakan-tindakan serta gerakan-gerakan jasmaniah dan material.
Pada saat yang sama, kata al-ikrah dalam ayat tersebut didahului dengan huruf la nafy li al-jins, yaitu huruf la yang berfungsi meniadakan segala sesuatu yang sejenis dan berkaitan dengan yang dimaksud secara harfiah dalam suatu ungkapan tertentu. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa segala bentuk tindak pemaksaan, pemasungan, penekanan, intimidasi dan semisalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sama sekali dilarang dalam hal beragama atau berkepercayaan.
Dengan kata lain, ayat ini meniadakan semua unsur keyakinan terhadap agama (kebaikan maupun keburukan), apa pun yang dilandaskan atas dasar paksaan. Karena agama berkaitan erat dengan pengetahuan ilmiah, berkaitan dengan i`tiqad, yakni keyakinan dan iman adalah urusan hati yang padanya tidak berlaku hukum paksaan dan tekanan dan selalu memiliki illat dan sebab lain yang bersifat nuraniah.
Muhammad Abduh menegaskan iman adalah unsur pokok dalam agama. Oleh karena itu, mustahil memaksakan iman dengan tekanan. Iman itu harus diiringi dengan penjelasan/keterangan (bayan) dan argumen-argumen, bukti-bukti yang mengokohkannya (burhan).
Maka ketika pernyataan la ikraha fi al-din diikuti dengan pernyataan qad tabayyana al-rusyd min al-ghayy, itu artinya telah tampak dengan jelas bahwa dalam agama-agama (al-milal) dan aliran-aliran (baca: kepercayaan-kepercayaan, al-nihal) itu ada irsyad, petunjuk, kebahagiaan, dan cahaya. Abduh tidak menunjukkan secara eksplisit tentang maksud al-milal dan al-nihal. Dari sini dapat dipahami bahwa agama apa pun yang dipilih sebagai jalan hidup, ada kemungkinan bagi penganutnya untuk memperoleh irsyad, petunjuk, kebahagiaan, dan cahaya darinya. Yang penting ada agama yang menjadi pegangan hidup, sandaran spiritual bagi manusia terhadap Realitas Ultim dan dengannya jalan keselamatan diharapkan tercapai.
Ayat tentang tidak ada paksaan dalam hal beragama dan berkepercayaan ini mengandung dua sudut pandang hukum: Pertama, hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikitpun untuk bergama. Kedua, hukum syariat melarang membebani atau menekan manusia untuk beriman dan berkeyakinan dalam situasi terpaksa.
Sesuai dengan hakikat pembentukan iman, paksaan akan menyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dorongan keyakinan batin atau nurani. Dalam segala urusan penting – lebih-lebih beragama – paksaan bertentangan dengan dua hal, yakni dengan kehendak Si Pembuat Perintah Yang Maha Bijaksana dan Pemelihara orang-orang berakal, yaitu Allah SWT, di mana tekanan tidak akan menyampaikan manusia pada terangnya masalah kebenaran (al-Haqq).
Paksaan juga bertentangan dengan rasio karena paksaan, taqlid, dan semacamnya tidak dapat menjelaskan aspek-aspek kebaikan dan keburukan, juga tidak memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki kebebasan memilih bagi dirinya sendiri, apa yang dikehendaki untuk dilakukan atau ditinggalkan, dan akibat-akibatnya yang baik maupun buruk.
Ahmad Mustafa al-Maraghi menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa memaksa manusia untuk beriman, selain berlawanan dengan kebebasan manusia (al-istiqlal), juga bertentangan dengan kehendak dan iradah Allah. Dengan demikian, wilayah iman berhubungan erat dengan wilayah etika.
Manusia tidak mungkin meyakini sesuatu tanpa memikirkan keyakinannya itu. Dan untuk itu tidak ada kewajiban bagi seorang muslim memaksa orang lain dalam berislam (baca: beragama/berkepercayaan).
Paparan itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam Islam. Orang tidak dipaksa untuk memeluk Islam, tetapi mereka diajak untuk merenungkannya dan jika mereka berpikir secara rasional, maka pasti mereka akan menerima Islam. Sebaliknya, jika ada paksaan, maka akan timbul pelanggaran atas pemikiran masyarakat dan problem kehidupan selanjutnya. Penguasa yang berkuasa berhak menegakkan undang-undang yang melindungi dan menjaga keberadaan mereka. Oleh karena itu, sistem ini akan menjamin perlindungan agama untuk tetap hidup dan berkembang. (Bersambung)
Artikel ini ditulis oleh Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., Rektor UIN Salatiga di solopos.com