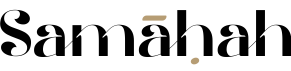Pengetahuan suci Al-Qur’an adalah inti dari pencarian ilmuwan dan filosof Muslim. Pengetahuan dan intelek dihargai dalam masyarakat, terutama pada periode kejayaannya, selama Dinasti Fatimiyah (909 M) dan Dinasti Moor Spanyol dan Andalusia (711-1300 M). Misalnya, Al- Khawarizmi (780-850 M) ilmuwan algoritma, dan Ibn Haytham (965-1039 M) pendiri optik sebagai bidang studi, dan di atas segalanya ialah Ibn-Sina bapak Kanon Kedokteran (Qanun fi al-Thibb), semuanya berkontribusi pada kemuliaan dan kemajuan intelektual zaman itu.
Banyak lembaga pendidikan, perpustakaan, dan rumah sakit dari Andalusia hingga Kairo dan Bagdad didirikan pada zaman keemasan Islam ini pada abad ke-8 sampai abad ke-13. Cendekiawan muslim, Fazlur Rahman, menyebutkan dalam Major Themes of the Quran bahwa pada saat penaklukan Saladin (1137-1193), pendiri dinasti Ayyubiyah, ia menemukan 1,6 juta buku di perpustakaan dinasti Fatimiyah lama (909-1171) di Kairo, yang mencakup lebih dari 18.000 manuskrip tentang mata pelajaran sains.
Saya melukiskan perhatian kepada tokoh-tokoh Islam bersejarah ini dan kontribusi ilmiah dan intelektual mereka untuk menyoroti bahwa nilai-nilai Islam dalam memperoleh pengetahuan dan menggunakan pengetahuan untuk mempromosikan pembelajaran dan mengembangkan kapasitas intelektual pada dasarnya didasarkan pada lanskap moral Al-Qur’an.
Secara historis, peradaban Islam telah mempromosikan perolehan pengetahuan dan penyelidikan alam. Pertumbuhan intelektual ini diuntungkan tidak hanya Muslim, tetapi juga orang-orang Yahudi dan Kristen, yang tinggal bersama dan di sekitar mereka. Peradaban ini menganut prinsip toleransi dan pluralisme.
Adapun mengenai pencarian/pengalaman mistik, menurut Ibnu Taimiyah, “pengetahuan yang benar” hanya terungkap kepada para nabi Allah, melalui apa yang disebutnya “wahyu”. Pengetahuan dicapai melalui wahyu-wahyu ini “lebih lanjut dipertahankan melalui zikir”, yang akan lebih dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui perenungan (tadabbur).
Refleksi, perenungan, dan kontemplasi dengan demikian semuanya dianggap sebagai ekspresi intuitif (`Irfan). Muhammad Arkoun mengkategorikan tema refleksi dan kontemplasi intuitif ini sebagai “menjadi” sadar, menembus, memahami, dan bermeditasi.”
Ia menegaskan bahwa pada dasarnya semua aktivitas ini merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, yang merupakan aspek fundamental dari intelek Ilahi. Pengalaman mistik Ilahi pertama Muhammad terjadi di Gua Hira, ketika dia menerima wahyu pertama Al-Qur’an. Level selanjutnya adalah pengalaman spiritual ke surga untuk menyaksikan ‘tingkat manifestasi tertinggi’ Tuhan, mikraj atau perjalanan spiritual yang dilakukan olehnya.
Dalam tasawuf, perjalanan ini adalah sebuah jalan kelanjutan dan lebih tinggi dari syariah, dan disebut Tariqah. Masalah syariah berkaitan dengan hukum Islam yang memberikan kerangka eksoteris (zhahir) masyarakat Islam. Dalam praktik Tariqah, hati dan jiwa atau dimensi esoterik (bathin) itu penting di atas aspek fisik tubuh manusia.
Pikiran manusia, atau lebih tepatnya, kebijaksanaan (hikmah), dipupuk melalui wahyu, berfungsi sebagai panduan menuju pengalaman spiritual seorang salik. Kontemplasi, refleksi, dan terhubung dengan Yang Ilahi adalah isi dari praktik Tariqah.
Kontemplasi adalah keajaiban spiritual. Ini adalah kekaguman spontan pada kesucian hidup, kesucian eksistensi. Ini adalah realisasi nyata dari fakta bahwa hidup dan eksistensi di dalam diri kita berasal dari yang tidak terlihat, transenden, dan sumber berlimpah tanpa batas. Kontemplasi di atas segala kesadaran akan realitas sumber itu.
Ia mengetahui sumber tanpa batas itu, sumber yang sangat samar, dan tidak dapat dijelaskan, tetapi dengan kepastian yang melampaui rasio dan melampaui iman yang sederhana.
Syed H. Nasr berpendapat bahwa hati (qalb) adalah tempat untuk menerima pengalaman langsung, sedangkan pikiran atau penalaran memiliki kapasitas pengetahuan tidak langsung. Ia merujuk pada hadits Nabi:
“Berbahagialah orang yang membuat hatinya terpejam.”
Sedangkan Al-Qur’an dan hadits keduanya memberikan ilmu kepada hati, seolah-olah hati adalah pembawa, atau ‘tempat kedudukan pengetahuan’. Pengetahuan ini adalah “bentuk pengetahuan tertinggi”, dan itu naik dari pengalaman sensual ke pengalaman spiritual. Nasr dengan indah menyatakan bahwa pikiran adalah cerminan hati, pusat mikrokosmos.
Doktrin Islam tentang tauhid telah merangkul semua mode mengetahui menjadi komplementer. Gnosis hati yang suci pada akhirnya tidak lain adalah pengetahuan yang menyatu dan menyatukan dari Yang Esa, dan realisasi paling mendalam dari Kesatuan (Tuhan), yaitu Alfa dan Omega dari wahyu Islam.
Dalam khazanah epistemologi Islam juga dikenal pendekatan `Irfani. Istilah `irfani berasal dari kata `irfan yang dalam bahasa Arab diderivasi dari kata `arafa, berarti mengetahui atau memahami. Kata `irfan yang setara dengan kata ma’rifah sangat dikenal di kalangan ahli tasawauf sebagai pemahaman yang mendalam dari hati Nurani, ilham atau sesuatu yang dapat membuka tabir yang menutup kehidupan batin.
Jika ditelusuri, kata `irfan mengandung beberapa arti, antara lain: ilmu atau ma’rifah, inspirasi dan kashf yang telah dikenal jauh sebelum Islam, dan al-ghanus atau gnosis. Ketika `irfan diadopsi ke Islam, para ahl al-`irfan memberikan kemudahan untuk berbicara tentang al-naql dan al-tawzif dan mengungkapkan wacana qur’ani dan memperluas ibarahnya untuk melipatgandakan makna.
Jadi pendekatan `irfani adalah pendekatan yang digunakan dalam kajian Islam di kalangan mutasawwifun dan dan ahli hikmah untuk melepaskan makna batin dari lafz dan ibarah. Pendekatan ini merupakan istinbat al-ma’rifah al-qalbiyyah dari Al-Quran.
Irfani sebagai metode untuk memperoleh ilmu yang benar melalui penampakan/pengalaman langsung kepada subjek disebut ma’rifah. Sarana untuk mencapai ma’rifah adalah hati, bukan akal atau logika. Hati yang dimaksud bukanlah bagian fisik dari tubuh, tetapi merupakan pemisahan ruhiyah Ilahi yang merupakan hakikat realitas manusia. Akal manusia belum mampu memahami bagaimana kerja intuisi dalam` irfani.
Pengalaman batin Rasulullah Saw menerima wahyu Al-Qur’an merupakan contoh konkret dari `irfani. Demikianlah prinsip wasathiyyah atau moderasi dalam Islam senantiasa mempertahankan keseimbangan antara pencarian intelektual-pengembaraan rasional dan pencarian mistik-pengalaman spiritual-intuitif. Cara beragama kaum Muslim semacam ini tidak lain bertujuan untuk mencapai kebenaran nalar dan intuitif secara bersamaan – memahami yang jelas, terang, riil, empirik dan terbatas (zhahir) dan menyelami hayati yang tersembunyi, transenden, tanpa batas (bathin).
Artikel ini ditulis oleh Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. di solopos.com