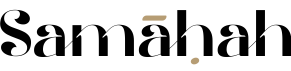Tradisi dan modernitas telah muncul sejak pertengahan tahun tujuh puluhan sebagai isu problematis utama dalam wacana budaya Islam dan Arab pada umumnya. Para pemikir telah berusaha untuk melihat tradisi masing-masing.
Mereka terbagi menjadi tiga aliran pemikiran: Pertama, penganut tradisi dengan penolakan yang hampir total terhadap modernitas, disebut sebagai ahl al-turath. Kedua, mereka yang menempatkan modernitas di atas tradisi karena tradisi dianggap sebagai suatu aspek dari kemunduran. Mereka disebut sebagai ahl al-hadathah. Ketiga, mereka yang mengadopsi rekonsiliasi antara tradisi dan modernitas di mana tradisi telah dipahami dalam konteks kontemporer (al-mu`ashirah).
Tradisi dan modernitas muncul sebagai fenomena ketika sebagian besar negara Arab memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Barat. Kritikus dan pemikir semacam Mohammed Arkoun dan M. Abid Al-Jabiri berpendapat bahwa masalah ini muncul dalam interaksi budaya yang tidak seimbang atau timpang antara Islam (bahkan Timur) dengan Barat karena banyak faktor yang ditopang oleh kemunduran dan pembusukan budaya dan kelemahan negara-negara dan budaya Arab pada umumnya.
Sebenarnya pertarungan antara tradisi dan modernitas itu merupakan peristiwa normal yang terjadi dalam ruang dan waktu, dan merupakan fenomena alamiah yang berkelanjutan dari masa lalu hingga kini dan seterusnya.
Beberapa karya yang tersedia tentang masalah ini secara khusus menunjukkan bahwa para pemikir Arab menggunakan dua kata itu untuk satu atau lebih tujuan berikut. Sebagian menggunakan istilah dualitas — tradisi-modernitas atau tradisi-kontemporer — untuk membedakan antara masa lalu dan masa kini.
Krisis Budaya
Sebagian lain menggunakan istilah itu untuk menyebut masalah sosial budaya. Sebaliknya, sebagian lain memandang pasangan (tradisi-modernitas) sebagai dua entitas: satu sebagai model dominan yang mendikte dan yang lainnya adalah replika. Yang lain merujuk pada frasa ini untuk menunjukkan proses di mana masa lalu terintegrasi dengan masa kini.
Namun, satu penggunaan umum dari istilah ini tampaknya mengaitkannya dengan masalah identitas dan krisis budaya. Makna ini muncul pada sebagian besar tulisan di mana para pemikir menyebut tradisi-modernitas, ashalah wa mu`ashirah, sebagai referensi untuk krisis budaya.
Untuk ini para pemikir menangani masalah ini dalam beberapa tingkatan. Sebagian menyelidiki tradisi dengan masalah budaya yang saling terkait pada tingkat terminologi. Lainnya mendeteksi pengaruh isu pada struktur sosial, budaya, ekonomi atau politik dunia Arab. Dan yang lain memperhatikan sejarah, sementara beberapa fokus pada pengaruh bahasa pada krisis yang muncul.
Akibatnya, ada tiga pendekatan utama untuk mengatasi masalah “tradisi versus modernitas” di dunia Arab/Islam: Pertama, mendukung tradisi. Kedua, menempatkan modernitas di atas tradisi. Ketiga, kompromi di antara keduanya. Mereka yang mengadopsi tradisi telah digambarkan sebagai kaum “tradisionalis” dan pendekatan mereka sebagai “konvensional” atau Salafiyyah.
Hassan Hanafi telah memperhitungkan pendekatan ini dan menunjukkan bahwa ia menghargai “tradisi” sebagai warisan suci yang berisi solusi ideal untuk masa lalu dan masa kini. Namun, dalam metodologi ini, Hanafi berpendapat, tradisi telah ditangani dengan cara yang berbeda: sementara sebagian berpegang teguh pada tradisi dan menolak modernitas sepenuhnya, yang lain lebih toleran selama tidak bertentangan dengan apa yang disebutnya “tradisi murni”.
Kelompok ketiga, lanjut Hanafi, lebih menganut pendekatan intelektual yang berusaha menafsirkan aspek-aspek kekinian dalam perbedaan dengan tema-tema tradisional. Metodologi ini, meskipun lazim terutama dalam studi agama, dikritik karena tidak mampu mengatasi perubahan yang muncul, sehingga melarikan diri kembali ke masa lalu, serta menjadi ahistoris dalam arti tidak memiliki pembacaan objektif dari masa lalu.
Kelompok yang menganut modernitas memandang tradisi sebagai bagian dari masa lalu yang mundur atau salah satu aspeknya. Mereka mengklaim bahwa hal itu tidak menambah kebaikan pada masa kini sehingga harus diabaikan sama sekali. Menurut Hanafi, pendekatan ini menguntungkan modernitas dan semua aspek yang berhubungan dengan contoh-contoh kemajuan dari industri Barat. Namun, pendekatan ini dikritik karena replika model internasional, mengabaikan pentingnya “identitas diri” budaya dalam konteks ruang dan waktu.
Rekonsiliasi
Kelompok ketiga mendamaikan tradisi dan modernitas. Abdul Basit Seeda telah menguraikan pendekatan ini dalam tesisnya dan berpendapat bahwa rekonsiliasi itu dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Pertama adalah rekonsiliasi eksternal dengan mengadopsi teori modern dan menerapkannya pada tradisi. Menurut Seeda, pendekatan ini juga digunakan oleh lulusan Arab dari universitas-universitas Barat.
Dia juga mengklaim bahwa ini terjadi secara tidak sengaja daripada sengaja karena tujuannya dalam banyak hal adalah untuk menarik perhatian orang tersebut daripada ide itu sendiri. Beberapa orang menyebutnya “kembalinya anak yang hilang”. Kedua, rekonsiliasi internal, yaitu mencocokkan aspek positif tradisi dengan kebutuhan zaman modern terkait transformasi sosial. Namun, ia mengkritik pendekatan ini sebagai eklektik.
Setelah pengenalan singkat ini, kita beralih ke pertanyaan: bagaimana tradisi versus modernitas menjadi isu penting dalam wacana Islam/Arab dan bagaimana ia berkembang?
Pemikir dan kritikus semakin menyadari masalah identitas yang memanifestasikan dirinya dalam aspek budaya setelah berakhirnya era penjajahan yang melanda dunia Arab. Salah satu penulis elite Arab yang menyoroti konfrontasi dan penundukan budaya Arab terhadap pengaruh Barat ini, menghasilkan sebuah masalah identitas adalah Edward Said.
Dalam bukunya “Orientalisme” yang diterbitkan kali pertama pada tahun 1979, Said mengemukakan bahwa konfrontasi lintas budaya antara Barat dan Timur lebih dari sekadar ekspedisi ilmiah yang mengeksplorasi aspek budaya. Dia menulis bahwa Orientalisme adalah sistem representasi, dibingkai oleh seluruh rangkaian kekuatan yang membawa Timur ke dalam kajian barat, kesadaran barat dan, kemudian kekaisaran barat.
Said secara kritis meninjau kekuatan pandangan penjajah tentang Timur dari abad ke-18, yang banyak penulis menganggapnya sebagai permulaan Orientalisme. Dia mendasarkan argumennya pada teori dominasi dan kekuasaan Michael Foucault, di mana Orientalisme adalah alat dominasi Barat atas dunia Islam/Arab.
Dia berargumen bahwa Orientalisme dalam sistem metodologi dasarnya hanya memandang bangsa-bangsa yang ditaklukkan sebagai makhluk antropologis untuk dipelajari dan dikendalikan. Dalam pengertian ini, gagasan Orientalisme hanyalah gagasan fungsional yang terintegrasi dengan sistem penjajahan secara keseluruhan.
Sejak diterbitkannya Orientalisme, para kritikus dan pemikir Arab telah berkontribusi pada masalah ini dengan cara yang berbeda. Banyak penulis memikirkan masalah identitas dan konfrontasi antara budaya asing dan budaya Arab yang inferior. Sementara beberapa penulis berusaha menganalisis situasi keterpurukan saat ini, dan penulis lainnya kembali ke masa lalu untuk memahami parameternya, yang memberikan banyak kepentingan untuk tradisi. Penulis di seluruh dunia Arab membahas pemikiran Islam Arab, evolusinya, pembentukannya, dan keadaan saat ini.
Artikel ini ditulis oleh Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., Rektor UIN Salatiga di solopos.com