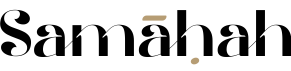Ide tentang maqashid al-Shariah atau tujuan hukum Islam yang lebih tinggi secara bertahap telah menarik perhatian banyak sarjana muslim kontemporer yang melihatnya sebagai metodologi untuk memecahkan masalah kekinian.
Gagasan ini memberikan pedoman dan kerangka kerja bagi proses ijtihad dalam upaya memecahkan masalah secara kreatif dengan tetap mematuhi kehendak Pemberi Hukum (Allah SWT). Dengan demikian, maqashid al-Shariah sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dapat dipandang tidak hanya sebagai doktrin atau prinsip hukum, tetapi lebih penting lagi sebagai falsafah hukum atau sistem nilai yang mengatur aturan-aturan hukum syariah dan mencerminkan pandangan dunia Islam dalam semua dimensinya.
Ibn Ashur mendefinisikan maqashid al-Shariah sebagai makna yang lebih dalam (ma`ani) dan aspek batin dari kebijaksanaan (hikam) yang dipertimbangkan Pemberi Hukum (Shari’) di semua atau sebagian besar wilayah dan keadaan undang-undang (ahwal al-tashri‘).
Ia juga menjelaskan pentingnya pengetahuan maqashid al-Shariah bagi para mujtahid, tidak hanya dalam memahami dan menafsirkan teks-teks syariah, tetapi juga untuk menemukan solusi atas masalah baru yang dihadapi umat Islam di mana teks-teks itu diam.
Pembahasan wasa’il sebagai sarana untuk mencapai maqashid belum pernah dibahas para ulama klasik sebagai kajian yang berdiri sendiri. Memang kata wasilah atau wasa’il ditemukan dalam literatur klasik ketika mendiskusikan topik al-sabab, muqaddimah al-wajib, dan lebih khusus lagi sadd al-dharai’.
Ibn Ashur telah mengamati hal ini dalam bukunya Maqashid al-Shariah, “Ini adalah subjek penting yang tidak ditangani para sarjana awal dengan memuaskan. Mereka membatasi diri pada sadd al-dharai’ di mana mereka menetapkan dhari’ah sebagai sarana dan apa yang dimiliki dhari’ah digunakan untuk mencapai tujuan (maqshad).
Namun, sebagian ulama dalam beberapa hal telah menjelaskan topik ini, khususnya Izz al-Din ibn Abdul al-Salam, diikuti oleh al-Qarafi dalam bukunya al-Furuq.
Maqashid al-Shariah dalam menghasilkan manfaat atau mencegah bahaya hanya dapat dicapai dengan mematuhi aturan Pemberi Hukum, dengan memenuhi sarana dan penyebabnya. Dengan demikian sarana atau wasa’il mengacu pada aturan (ahkam) yang ditetapkan Pemberi Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan.
Dengan demikian, sarana atau wasa’il tidak dimaksudkan untuk kepentingan sarana itu sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lain dengan cara paling tepat. Tanpa sarana/wasa’il, tujuan syariah mungkin sama sekali tidak tercapai atau tidak tercapai sepenuhnya.
Perbuatan Halal
Salah satu contoh yang disebutkan oleh Ibnu Ashur adalah kepemilikan (hawz) properti dalam akad al-rahn (hipotek) yang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memenuhi prinsip gadai dan untuk menjamin keamanan utang sehingga pemberi hipotek (rahin) tidak akan menjaminkannya kepada kreditur lain sehingga mengabaikan hipotek pertama. Sedangkan al-Qarafi mendefinisikan wasa’il sebagai jalan menuju maqashid. Menurut Ibnu Qayyim, wasa’il ialah segala sesuatu yang merupakan sarana atau jalan menuju sesuatu; Ibnu Katsir mengatakan wasa’il itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan.
Karena dhari’ah selalu membayangi diskusi para ulama tentang wasa’il, maka sangat penting membahas dhari’ah. Kata dhari’ah (jamak: dharai’ ) menandakan sarana atau cara untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, secara linguistik dharai’ identik dengan wasa’il. Namun secara teknis, ada dua posisi dalam mendefinisikan makna dharai’ sebagai sumber derivasi hukum.
Pertama, pandangan sebagian besar ahli hukum klasik bahwa dharai’ dalam arti sempit menunjukkan cara-cara atau sarana yang halal tetapi bisa mengarah pada tujuan yang dilarang atau hasil yang melanggar hukum. Ibn Rusyd mendefinisikan dharai’ sebagai hal-hal yang tampaknya diperbolehkan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk sesuatu yang dilarang.
Menurut Imam al-Shatibi, dharai’ adalah menggunakan kemaslahatan (maslahah) sebagai sarana untuk mencapai hal yang merugikan (mafsadah). Jadi, dharai’ berarti melarang tindakan yang halal karena kemungkinan mengarah pada hasil yang melanggar hukum.
Penting untuk disebutkan bahwa tidak semua perbuatan hukum harus dilarang atas dasar kemungkinan bahaya yang timbul darinya. Dalam hubungan ini para fuqaha membagi perbuatan halal menjadi tiga kategori: a) Yang jarang menimbulkan akibat merugikan, seperti menanam anggur yang jarang menghasilkan anggur; b) yang biasanya mengarah pada hasil yang berbahaya, seperti penjualan anggur ke kilang anggur dan penjualan senjata kepada penjahat; c) yang menimbulkan kemungkinan sama baik bahaya maupun manfaatnya. Misalnya, menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menceraikannya agar dia dapat menikah lagi dengan mantan suaminya.
Kedua, mendefinisikan dharai’ dalam arti yang lebih luas dan mencakup semua cara, apakah itu mengarah pada hasil yang berbahaya atau yang bermanfaat. Ini berarti mencegah segala cara yang mengarah pada konsekuensi yang merugikan (sadd al-dharai’) atau membuka dan mendorong semua cara yang mungkin untuk tujuan yang bermanfaat (fath al-dharai’).
Beberapa ahli hukum klasik dan mayoritas ulama kontemporer mengambil posisi ini. Perlu dicatat di sini bahwa meskipun para ahli hukum klasik sepakat tindakan yang bermanfaat harus didorong, namun mereka tidak memberikan penekanan yang cukup pada aspek ini dalam diskusi mereka.
Sebaliknya, mereka fokus pada sadd al-dharai’ atau menghalangi sarana. Pencegahan kejahatan harus lebih diutamakan dalam diskusi mereka.
Segala Cara
Pembukaan sarana untuk kebaikan (fath al-dharai’) tidak menerima perlakuan yang sama dari para ahli hukum dalam tulisan-tulisan mereka. Penjelasannya adalah bahwa fath al dharai’ ketika sarana dan tujuannya sama-sama diarahkan pada kemaslahatan yang halal (maslahah) itu termasuk dalam aturan umum syariah dan jika tidak diatur secara eksplisit oleh nass, itu akan termasuk dalam lingkup topik lain.
Namun, para ahli hukum seperti al-Imam al-Qarafi melihat dharai’ dalam arti luas. Ia mendefinisikan dharai’ sebagai segala cara yang mengarah ke tujuan tertentu.
Ia menambahkan dharai’ harus diblokir ketika mengarah pada hasil yang melanggar hukum; juga perlu dibuka karena mungkin diperlukan (wajib), menjijikkan (makruh), dianjurkan, atau diperbolehkan (mubah). Demikian pula, dharai’ hanya menunjukkan sarana. Oleh karena itu hanya sarana maka untuk apa yang dilarang harus dilarang, demikian juga sarana untuk apa yang wajib juga menjadi wajib.
Definisi dharai’ yang luas dan komprehensif ini dan mencakup aspek sadd al-dharai’ dan fath al-dharai’ yang telah diadopsi sebagian besar ahli hukum kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhayli, Abdullah al-Juday’, dan lainnya.
Perlu dicatat bahwa definisi wasa’il identik dengan dharai’ dalam arti luasnya dan telah diadopsi banyak ulama dalam karya mereka. Al-Qarafi menyatakan dhari’ah sebagai wasilah terhadap sesuatu. Hukum itu dapat dibagi menjadi dua: maqashid yang terdiri atas manfaat dan bahaya dan wasa’il yang merupakan sarana untuk mewujudkan maqashid lalu hukum wasa’il mengambil aturan yang sama dengan apa yang mereka pimpin, apakah itu dilarang atau diizinkan.
Ibn Asyur setuju dengan al-Qarafi, tetapi pada saat yang sama mengikuti mayoritas dalam berurusan dengan dharai’, sementara dia menyatakan, “Jika bukan karena istilah sadd al-dharai’ telah ditentukan untuk mencegah cara yang mengarah pada kerusakan, kami akan mengatakan bahwa syariah memblokir sarana itu juga membuka sarana lain.”
Artikel ini ditulis oleh Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., Rektor UIN Salatiga di solopos.com